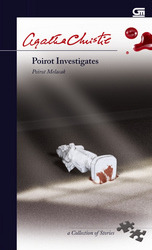TEMPO, 148 halaman
6 Juli 2015
6 Juli 2015
ISBN13 9789799108913
Seperti halnya pendapat bahwa 'tidak ada orang yang benar-benar asli Indonesia', dalam hal kuliner juga bisa dibilang tidak ada masakan yang benar-benar asli Indonesia. Sederhana saja, negara ini terbentang begitu luas, dengan keanekaragaman yang nyaris tidak terhitung, tidak ada jenis masakan yang benar-benar bisa merangkum dan merengkuh semua itu. Sejarah padi di negara ini saja terhitung masih 'muda' jika dibandingkan dengan Asia Timur.
Buku ini kemudian berniat untuk membahas 'tingkah laku' kuliner Indonesia yang beragam ini, dan saya kutip: "...menelusuri 'peradaban rasa' itu dari tumpukan manuskrip kuno hingga ke jantung belantara di pulau-pulau yang jauh. ..."
Pada bagian awal, untuk memulai diskusi, dimulai dengan Ternate dan Tidore; salah satu daerah penting dalam hal sejarah rempah dunia. Dari segi penyajian (ahem), buku ini terbilang cukup menarik. Foto-fotonya tertata dengan baik, menarik mata, dan yang terpenting: sungguh menarik selera.
Tapi sayangnya, selera ini kemudian semakin menurun seiring bertambahnya jumlah halaman yang dibaca. ...
Layout-nya yang sederhana tapi berwarna memang tidak berubah, namun semakin lama saya semakin merasa buku ini lebih terasa seperti laporan travelling, dengan tips-tips wisata kulinernya. Memang tidak terlalu salah, tapi saya mengharapkan sedikit lebih banyak dari buku yang mempunyai subjudul "Ekonomi, Politik, dan Sejarah di Belakang Bumbu Makanan Nusantara"..
Ataukah buku ini hanya mencantumkan kata 'Antropologi' dalam judulnya sebatas untuk trik dagang saja?
Memang bukan tinjauan akademis berlibet-libet penuh daftar pustaka yang saya harapkan, tapi paling tidak ada tinjauan lah.. Banyak info singkat dalam buku ini yang diulang-ulang, bahkan dalam jarak kurang dari dua paragraf.
Kajian antropologis--yang secara umum berarti kaitan manusia dan kebudayaan yang dihasilkannya--juga nyaris nihil. Cerita historis, cerita lokal, lalu apa? Tidak ada usaha untuk mengaitkan info-info singkat ini.
Beberapa bagian juga terasa disimplifikasi, seperti Jawa = Solo = Jogja = keraton = manis. Padahal Solo dan Jogja, meskipun letak geografisnya sungguh begitu dekat, tetapi ada beberapa poin-poin kebudayaan yang menurut saya tidak boleh dilewatkan begitu saja. Misalnya pengaruh pendatang Cina dan Arab yang sangat besar di Solo. Tentu poin-poin ini sedikit banyak juga berpengaruh penting dalam kultur kuliner kedua kota.
Satu lagi titik lemah dalam buku ini: kalau berbicara tentang kuliner, tentunya bukan hanya tentang lidah dan perut saja. Tata cara penyajian sebuah masakan, atau tipe makanan dalam suatu kebudayaan pasti ada latar belakang historis dan sosialnya. Misalnya, apakah pisang rebus yang biasa dimakan sebagai snack di angkringan sama dengan pisang rebus yang dimakan sebagai pendamping makanan utama di daerah Sulawesi atau Maluku?
Sebagai tinjauan antropologi, buku ini sangat mengecewakan. Tetapi, sebagai penggugah pengetahuan, buku ini cukup lumayan. Paling tidak cerita-cerita menarik, deskripsi makanan yang begitu detil, dan juga tips wisata yang ada, mungkin bisa membangkitkan kesadaran orang bahwa kuliner Indonesia jauh, jauh, jauh, lebih banyak dari sekedar nasi dan gorengan saja.
Ke depannya, saya juga berharap bahwa para penulis bisa mengkaji kuliner Nusantara dengan jauh, jauh, jauh, jauuuh lebih baik, lebih besar, dan lebih luas. (Papua!!)